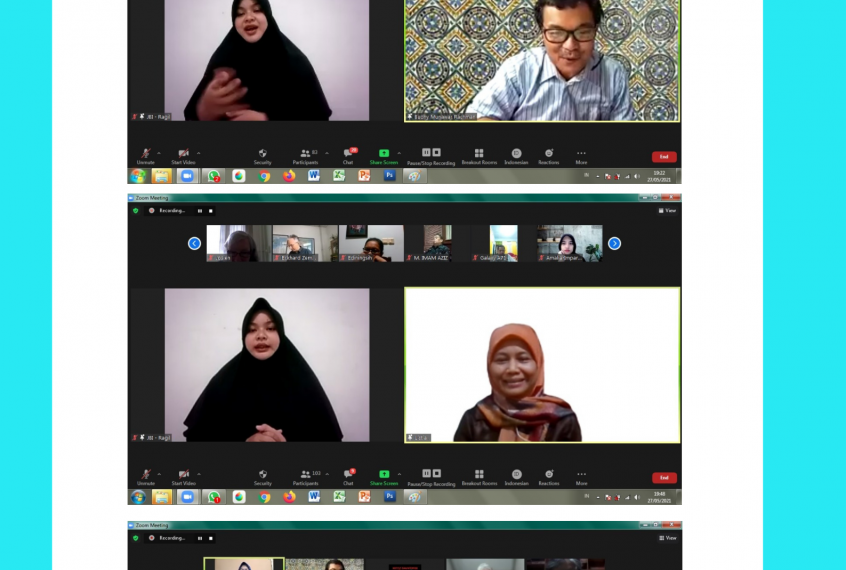Pendeta Tigor Yunus Sitorus, Berjuang untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Bangunan Gereja seluas 7x4 meter itu terlihat lengang. Kursi-kursi yang tersusun di pojok ruangan nampak berdebu sebab sudah terlalu lama tidak ada yang menggunakannya untuk ibadah pasca pandemi Covid-19 terjadi. Pendeta Tigor Yunus Sitorus (50) dan istrinya, Pendeta Deborah Sundari (47), sedang bersiap-siap memimpin ibadah minggu pagi secara online.
Ibadah dimulai dengan menyayikan lagu puji-pujian dari Alkitab. Pendeta Deborah berdiri menghadap jemaatnya di layar gawai dan mulai bernyanyi dengan penuh penghayatan. Sementara itu Pendeta Sitorus mengetik guitar dan dibantu anak lelakinya untuk memainkan piano. Anak lelakinya yang bungsu membantu mengambil gambar proses ibadah. Begitulah suasana ibadah daring di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Imamanuel Sedayu.
Bangunan GPdI Immanuel Sedayu berada tepat dan menempel dengan bangunan rumah Pendeta Sitorus di Dusun Bandut Lor, RT 034, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta. Aula peribadatan yang sederhana itu cukup menampung sekitar 80-an hingga 100 Jemaat, dengan altar kecil di depannya dan salib berukuran sedang yang menempel di tembok.
Pada tahun 2003, rumah Pendeta Sitorus juga pernah digunakan sebagai Gereja. Namun hal tersebut dipersoalkan oleh warga. Bahkan menurut Pendeta Deborah, rumahnya yang sederhana waktu itu dirobohkan.
“Warga mempermasalahkan antara ijin tinggal dan ijin ibadah.” Jelas Pendeta Sitorus.
Menurut Pendeta Sitorus, konsep gereja lebih berkaitan dengan manusia atau lebih sebagai sebuah persekutuan (perkumpulan) manusia. Kemudian perkumpulan itu disebut sebagai organisasi dalam arti lembaga. Keberadaan sebuah Gereja harus tertib. Tidak hanya tertib dalam urusan beribadah tetapi juga tertib secara legal administratif.
“Karena kita hidup di Negara, secara tidak langsung kita wajib patuh dengan konstitusi, untuk itu saya mengusahakan surat ijinnya, sehingga bangunan ini legal.” Paparnya.
Setelah peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 tersebut, Pendeta Sitorus mulai melakukan upaya-upaya administratif sekitar tahun 2017 guna legalitas Gereja yang dilayaninya. Ia berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 98 tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Tempat Ibadat hingga akhirnya pada tahun 2019 Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dengan nomor ijin 0116/DPMPT/212/I/2019. Namun IMB tersebut dipersoalkan oleh warga. Mereka menolak adanya Gereja karena dianggap meresahkan. Pemkab Bantul melalui Surat Pemutihan dengan nomor 345 tahun 2019 membatalkan IMB yang mereka terbitkan. Pendeta Sitorus melakukan gugatan terhadap Pemda Bantul atas surat tersebut dan dibantu oleh solidaritas lintas iman dan LBH Yogyakarta.
“Waktu saya melakukan gugatan itu, ada teman-teman ANBTI (Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika) dan Srikandi Lintas Iman yang menemani, hingga akhirnya bersama Mas Budi Hermawan dari LBH Yogyakarta.” jelasnya.
Pembatalan tersebut dinilai melanggar Pasal 28 I dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan atas kebabasan beragama di Indonesia. Gugatan yang dilayangkan oleh Pendeta Sitorus akhirnya menempuh “jalan damai” atas kesepakatan beliau sendiri dengan Bupati Bantul. Pemerintah meminta kerelaan Pendeta Sitorus untuk melakukan relokasi pembangunan GPdI Sedayu yang semula berada di rumahnya di Dusun Bandut Lor Pindah ke Dusun Jurug, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Bantul, tiga kilometer dari tempatnya semula. Tanah seluas 246 meter itu dibeli oleh Pendeta Sitorus dan masih berupa lahan tegalan. Beliau mengungkapkan bahwa pendirian gereja ini akan dimulai dari nol. Sementara ia mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja secara fisik, ia akan terus melakukan silaturahmi kepada warga. Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah juga ikut mengawal sebaiamana kesepakatan damai yang dilakukan.
“Jangan sampai sudah ada ijin dan lain-lain, dicabut lagi, dan dipermasalahkan lagi di kemudian hari. Saya tidak mau. Kita ingin beribadah bersama jemaat di dalam rumah ibadah dengan khusyuk dan tetap bisa menjaga persaudaraan dengan warga di sekitar gereja.” Terangnya.
Ditemui secara terpisah, 20/11/20, Elga Sarapung, Direktur Institut Dian/Interfidei menyatakan keberatannya tentang hasil akhir sidang penyelesaian IMB GPdI Sedayu. Menurutnya “jalan damai” yang ditawarkan oleh pemerintah dalam artian relokasi Gereja bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, setiap kasus penolakan rumah ibadah, bukan hanya gereja, tetapi juga pura dan masjid selalu berakhir dengan “jalan damai” versi negara. Hal tersebut tidak membantu masyarakat menemukan akar permasalahannya.
"Jika setiap kasus diselesaikan dengan ‘jalan damai’, kasus-kasus tersebut berpotensi akan terus berulang. Dan itu sangat tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi kita. Kita memerlukan suatu solusi yang betul-betul menyentuh akar persoalannya dan bisa menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun.” jelasnya.
Sementara itu, Pemuda Lintas Iman Jogja, sekaligus Ketua Simpul Iman Community, (06/12/20) FX. Merry Christian Putra, menganggap bahwa setiap orang dengan latar belakang agama apapun pasti membutuhkan rumah ibadah. Dalam konteks beragama, menurut Christian, kita butuh ruang untuk ibadah dan bertemu Tuhan. Kita butuh tempat untuk mengungkapkan keimanan dan rasa syukur kepada-Nya. Sebagai pribadi yang hidup dalam negara, kita sepakat hidup dalam keberagaman agama. Negara itu kan sudah mengakui dan melegalkan semua agama, maka setiap warga negara harus menerima dan menghargainya dengan tulus. Adapun kehendak mendirikan rumah ibadah, itu menjadi hak setiap orang yang beragama di Indonesia untuk membuat surat ijin.
“Apabila ijinnya sudah keluar harus kita hormati bersama. Penentangan terhadap pembangunan rumah ibadah tidak dapat dibenarkan. Sebagai warga negara kita harus menjadi masyarakat yang tulus dan ikhlas dalam kehidupan keberagamaan yang beragam.” terangnya.
Pahit Manis Perjalanan Pendeta Sitorus dalam Menginjil
Niat tulus dan perjuangan Pendeta Sitorus tidak terlepas dari sosoknya yang memang sudah mengecap pahit manisnya berdakwah (menginjil). Ia mengisahkan perjalanannya menjadi seorang Pendeta hingga akhirnya memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi riak-riak dalam prosesnya menjadi penggembala (sebutan lain bagi pendeta). Ia mengisahkan perjalannya menjadi Pendeta, dimulai dari sebuah sekolah menengah Kristen di Sumatera Utara, lalu melanjutkan ke pendidikan tinggi di Akademi Theologia Alkitab Salatiga (sekarang STT Salatiga), lalu dilanjutkan dengan melakukan pengabaran injil di Pemalang, lalu ke Salatiga, kemudian di Kadipiro, hingga akhirnya menetap di Yogyakarta.
“Saya kurang paham juga bagaimana saya menjadi Pendeta, tetapi yang paling saya ingat waktu kecil itu, ada sesuatu yang mendorong saya menjadi pendeta. Sulit saya ungkapkan. Mungkin itu yang dikatakan oleh orang-orang sebagai “panggilan hati”, sehingga keseluruhan proses saya belajar membimbing saya menjadi seorang Pendeta.” Kenang Pendeta Sitorus.
Menurut Pendeta Sitorus, kebutuhan akan sebuah bangunan rumah ibadah pasti dimiliki oleh semua penganut agama apapun. Tidak terkecuali orang-orang Kristen. IMB menjadi sangat penting baginya sebab itu merupakan bukti bahwa Negara mengakui keberadaan keyakinannya.
“Rumah ibadah itu ‘kan bukan hanya sekedar bangunan, melainkan ruang dimana pembinaan spritual dilakukan. Pasti itu semua keyakinan menghendakinya. Kita punya ritual-ritual yang harus dilakukan secara kolektif (bersama), seperti perjamuan kudus, itu membutuhkan Pastor” Jelas beliau yang telah melayani gereka sejak tahun 1996 ini.
Secara keorganisasian GPdI merupakan gereja yang berkembang di Sumatera Utara pada tahun 1930-an. Seiring berjalannya waktu umat atau jemaat GPdI menyebar ke berbagai penjuru Indonesia. Sehingga pengikutnya berasal dari beragam latar belakang daerah. Pendeta Sitorus diutus untuk melayani di Yogyakarta sejak tahun 1997. Rata-rata jemaat berasal dari luar Yogyakarta, yaitu orang-orang rantau dan mahasiswa yang datang studi.
“Kalau sekarang-sekarang ini banyak mahasiswa Papua. Saya sendiri sangat senang, karena bisa dekat secara emosional dengan mereka. Tidak hanya mendorong mereka dalam soal spiritual, tetapi juga bisa menjadi orang tua kedua bagi mereka di sini.” Ujarnya.
Ada sekitar 20-an mahasiswa Papua yang menjadi jemaat di GPdI Sedayu Bantul. Suara-suara sumbang yang muncul dalam penolakan GPdI Immanual di antaranya adalah stigma terhadap teman-teman mahasiswa Papua. Menurut Pendeta Sitorus pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang bijak.
“Kita tidak bisa menolak orang-orang yang hendak beribadah. Apalagi kita sebagai anggota Gereja berasal dari denominasi (aliran atau mazhab) yang sama.” Imbuhnya.
Pendeta Sitorus mengatakan bahwa dari peristiwa penolakan gereja ini ia belajar memang tidak mudah dalam berdakwah. Ia menerima keseluruhan proses tersebut sebagai bimbingan dari Tuhan, bahwa setelah kejadian ini beliau terdorong untuk membangun dialog dan aktif melakukan sowan ke masyarakat di sekitar.
“Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalag dalam kehidupan bermasyarakat.” Ujarnya.
Peristiwa penolakan IMB GPdI Immanuel Sedayu memang menambah daftar panjang kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Pendeta Sitorus sendiri mengatakan bahwa ini pertama kali bagi dirinya mengalami perjuangan panjang dalam mengusahakan rumah ibadah bagi jemaatnya. Ia menceritakan bahwa selama proses bahkan setelah putusan pengadilan ia tidak menaruh dendam dengan orang-orang yang menolak gerejanya. Ia justru ingin memulai lembaran baru bersama warga di sekitar rumahnya.
“Saya tidak ingin mengungkit-ungkit lagi yang sudah berlalu. Saya ingin membuat lembaran baru bersama warga.” Ujarnya.
Ia bersyukur saat terkena Covid - 19 waktu lalu, beberapa warga mengirim makanan untuk kedua anaknya selama ia melakukan isolasi di rumah sakit. Pendeta Sitorus juga sudah melakukan bakti sosial sebelum pandemi di lokasi Gereja yang baru. Ia berharap, kehidupan yang beragam di dusunnya bisa rukun-rukun dan baik satu sama lain.
*Liputan ini merupakan hasil Fellowship Liputan Narasi Keberagaman yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta
Penulis : Ruwaidah Anwar
Editor : Haris Firdaus